Malari di Pusaran Isu Kudeta dan Tuntutan Kemandirian Ekonomi
Berawal dari kritik mahasiswa terhadap pemerintah yang membuka pintu untuk modal asing kemudian berubah menjadi penolakan terhadap kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka hingga terjadi huru-hara di Jakarta dan berakhir dengan tindakan represif pemerintah terhadap organisasi masyarakat maupun organisasi mahasiswa.
Siang ini mendung menyelimuti kawasan Proyek Senen, Jakarta Pusat. Persimpangan kawasan tersebut kini semakin estetik dan instagramable pasca direnovasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilengkapi dengan lintas bawah (underpass). Perlahan kemacetan dan keruwetan kawasan Senen yang telah menjadi pemandangan sehari-hari di salah satu pusat kegiatan perekonomian di Jakarta tersebut mulai terurai. Bila hari ini lalu lalang Bus Transjakarta dan dinamika kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 menjadi pemandangan di kawasan Proyek Senen, beda halnya dengan pemandangan Proyek Senen 47 tahun yang lalu. Pada Selasa, 15 Januari 1974, kawasan yang dibangun dengan anggaran milyaran rupiah ini menjadi saksi bisu terjadinya peristiwa huru-hara, penjarahan, dan pembakaran produk-produk made in Japan.
Kondisi mencekam yang terjadi di Jakarta merupakan bentuk protes terhadap kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka pada 14 Januari 1974 hingga 17 Januari 1974. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Malapetaka 15 Januari (Malari). Sejatinya Malari merupakan puncak gunung es akibat ketidakpuasan rakyat yang diwakili oleh mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang membuka pintu lebar bagi masuknya modal asing. Malari juga disinyalir menjadi puncak persaingan antara orang terdekat dipusaran kekuasaan Presiden Soeharto, yaitu Ali Moertopo dan Jendral Soemitro.
Pasca jatuhnya Presiden Soekarno dan pemerintahan Orde Lama, Presiden Soeharto yang membawa gerbong pemerintahan Orde Baru mewarisi hutang dan inflasi yang sangat besar. Pemerintah kemudian mengambil langkah taktis dengan membuka masuknya investasi asing yang sebelumnya ditutup rapat oleh pemerintah Orde Lama. Mulai dari Adam Malik hingga Sri Sultan Hamengkubuwono IX berupaya mempromosikan Indonesia di luar negeri. Presiden Soeharto pun berupaya melakukan perdamaian dengan Malaysia dan bergabung kembali menjadi anggota PBB.
Fokus utama pemulihan perekonomian diupayakan melalui perdamaian dengan negara sekitar dan memelihara stabilitas keamanan. Fundamental ekonomi menjadi perhatian, terutama bagi Soemitro Djojohadikusumo, Widjojo Nitisastro, dan kawan-kawan yang disebut dengan istilah Mafia Berkley. Pundi-pundi investasi mulai mengalir deras ke Indonesia berkat para ekonom handal tersebut. Perlahan perekonomian Indonesia kembali berdenyut dan mengalami pertumbuhan.
Memasuki tahun 1970, pemerintah mulai percaya diri terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan pemerataan dan upaya Indonesianisasi terhadap aset maupun modal asing sehingga gap antara si kaya dan si miskin tetap terjadi di tengah-tengah masyarakat. Denyut perekonomian yang cenderung mengarah pada kapitalisme memicu timbulnya persaingan terutama di pusaran pemerintahan. Ali Moertopo dan Jenderal Soemitro menjadi dua tokoh yang disinyalir terlibat persaingan sengit guna menjadi orang terdekat Presiden Soeharto. Sejalan dengan hal tersebut, korupsi juga tumbuh subur.
“Bangsa kita sudah menjadi kapitalis besar yang mengejar keuntungan dan pertumbuhan tanpa melihat aspek sosial. Kita hanya bicara soal pasar seakan pasar bisa mendistribusikan kekayaan,” ungkap Hariman Siregar. Kegamangan terhadap pemerintahan mulai dirasakan tidak hanya oleh Hariman Siregar, melainkan pula oleh J.C. Poncke Princen, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, termasuk oleh para mahasiswa untuk melayangkan kritik.
Adanya asisten pribadi presiden disinyalir memicu munculnya persaingan tidak sehat di lingkungan terdekat presiden. Tidak hanya itu, korupsi dan harga yang melambung tinggi menjadi fokus perhatian para pengkritik pemerintah. Sebenarnya aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia belum besar jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura pada periode tersebut. Namun, pemerataan yang tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat membuat munculnya protes. Isu-isu tersebut tidak hanya pada tatanan akar rumput melainkan sudah sampai ke permukaan, bahkan ke telinga presiden Soeharto. Akan tetapi, aliran investasi asing tetap masuk ke Indonesia, seakan tidak peduli dengan gelombang kritik dan protes yang digawangi oleh mahasiswa.
Sebagai kekuatan ekonomi baru pasca perang dunia II, Jepang mulai mengembangkan perekonomian dan berupaya menanamkan investasi melalui perusahaan-perusahaan multinasionalnya. Indonesia menjadi salah satu bidikan Jepang guna menanamkan investasi. Gayung pun bersambut, Indonesia yang sangat mengincar pertumbuhan menerima keinginan Jepang untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Wujud nyata upaya tersebut adalah kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Jakarta guna membahas kerjasama.
Beberapa hari sebelum peristiwa Malari tepatnya pada 11 Januari 1974, mahasiswa yang dikomandoi oleh Hariman Siregar menemui Presiden Soeharto di Bina Graha, Jakarta. Para mahasiswa kemudian menyampaikan kritik terhadap pemerintah yang dikenal dengan Tritura Baru, yaitu Bubarkan Asisten Pribadi Presiden, Turunkan Harga, dan Ganyang Korupsi. Tuntutan ini kemudian menjadi pintu gerbang aksi-aksi protes yang lebih keras terhadap pemerintah yang diwujudkan melalui diskusi hingga long-march.
Diskusi yang lebih sistematis kemudian dilakukan di Kampus Trisakti pada 15 Januari tersebut. Kemudian mahasiswa menuju kampus UI Salemba. Di lain pihak, beberapa kelompok mahasiswa berupaya mencegah iring-iringan Perdana Menteri Tanaka di Halim. Namun, upaya tersebut digagalkan oleh tentara yang berjaga di kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma. Kelompok ormas dan mahasiswa kemudian melakukan aksi long-march sebagai bentuk protes terhadap kedatangan Perdana Menteri Negara Matahari Terbit tersebut.
Unjuk rasa kemudian berubah menjadi huru-hara dan penjarahan. Kawasan Proyek Senen menjadi sasaran penjarahan. Bahkan proyek yang dibangun dengan biaya milyaran rupiah ini dibakar sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah yang tetap membuka kran investasi asing. Pada Selasa kelabu tersebut, sebanyak 807 kendaraan buatan Jepang ludes dilalap si jago merah, 11 orang meninggal dunia, 300 orang luka-luka, 144 bangunan rusak berat, dan sekitar 160 kg emas hilang dari toko perhiasan.
Pasca peristiwa Malari ini, investasi Jepang tetap mengalir ke Indonesia. Upaya pertumbuhan tetap menjadi fokus utama bagi pemerintah. Di sisi lain, pemerintah menganggap peristiwa Malari sebagai upaya mengkudeta kedudukan Presiden Soeharto sehingga pengkritik yang dikenal lantang menyuarakan aspirasi diganjar dengan hukuman penjara, seperti Hariman Siregar, J.C. Poncke Princen, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan Adnan Buyung Nasution. Sekitar 775 aktivis pun merasakan tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, dua kubu yang bertikai, yaitu Jendral Soemitro dan Ali Moertopo kemudian dipinggirkan dari lingkungan terdekat Presiden Soeharto.
Pemerintah pun kemudian mulai mencanangkan Nasionalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kampus (BKK) guna meredam politik hingga kritik yang berasal dari kampus maupun akademisi. Tindakan-tindakan represif tersebut kemudian membungkam upaya kritik terhadap pemerintah yang di kemudian hari justru menjadi bumerang bagi pemerintah Orde Baru. Sekali lagi peristiwa sejarah memberikan cerminan bahwa investasi asing perlu dibarengi dengan upaya alih daya, alih modal, dan Indonesianisasi sehingga pemerataan ekonomi dapat diwujudkan, tidak hanya semata berpijak pada upaya mengejar pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan kita semua bahwa upaya menutup kritik justru memicu pada dua hal, yaitu antipati rakyat dan degradasi kepercayaan terhadap pemerintah.












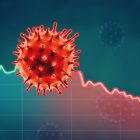



Recent Comments