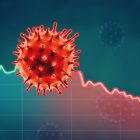Suatu hari, seorang calon pegawai kantoran sedang melaksanakan proses interview kerja oleh kepala bagian HRD.

***
Sebanyak 7 dari 10 orang perempuan yang saya wawancarai sebelum menulis artikel ini, menyampaikan bahwa pertanyaan wawancara kerja yang berkaitan dengan rencana menikah dan opsi memilih keluarga atau pekerjaan, adalah pertanyaan yang paling sering dipertanyakan oleh pewawancara kerja hingga saat ini di Indonesia. Secara implisit, dapat dikatakan bahwa pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang mengarah pada peran, tanggung jawab, serta relasi sosial dengan pelabelan menurut jenis kelamin (stereotip gender). Padahal sejak tahun 2013, pertanyaan tersebut bahkan sudah tidak lagi masuk ke dalam the 50 most common interview questions versi majalah Forbes.
Adapun jawaban yang disampaikan oleh interviewee dalam ilustrasi di atas merupakan jawaban yang – walaupun saya tidak yakin pernah disampaikan oleh seseorang atau tidak – selain bisa menjadi inspirasi jawaban interview Anda, juga merupakan pengantar yang menurut saya cukup holistik dalam membahas emansipasi wanita dan isu seksisme di lingkungan pekerjaan, baik dari sudut pandang ilmiah secara singkat (dalam hal ini neurologi) maupun secara sosiologis. Namun, dalam artikel ini saya berupaya untuk mengelaborasi isu seksisme di lingkungan kerja tidak hanya dari 2 (dua) sudut pandang di atas, tetapi juga dari aspek institusional dan teoritis.
Glorifikasi Perempuan dalam Selebrasi maupun Institusi
Sebagaimana kita ketahui bahwa perempuan selalu memiliki hari perayaannya yang digaungkan di seluruh penjuru negeri. Dunia internasional memiliki International Woman’s Day yang dirayakan setiap tanggal 8 Maret untuk memeringati hari demonstrasi para buruh perempuan di New York tahun 1908, yang pada saat itu menuntut hak mereka untuk berpendapat dan berpolitik. Di dalam negeri, Indonesia punya Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April. Hari Kartini menyorot perjuangan R.A. Kartini, seorang wanita terpandang anak Bupati Jepara yang walaupun dengan kedudukan priyayi-nya namun tetap memerjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki di masa itu melalui surat-suratnya. Selaras dengan tanah air, India juga mempunyai Hari Perempuan Nasional setiap tanggal 13 Februari untuk memeringati hari kelahiran Sarojini Naidu, seorang gubernur wanita pertama di India, penyair, aktivis perempuan, dan sosok inspiratif atas perjuangan hak-hak perempuan di tanah dharma cakra tersebut.
Gambar 1: Seorang laki-laki yang ikut menyuarakan aspirasi saat long march dari Hotel Sari Pasific, Sarinah hingga Taman Aspirasi dalam acara Women’s March Jakarta 2019 (Sumber: Ultimagz, 2019)
Tidak hanya bentuk perayaan untuk menyuarakan kesetaraan hak dan kedudukan perempuan, hari ini sebagian besar negara di dunia bahkan sudah melembagakan urusan perempuan yang juga dijamin oleh konstitusi. Indonesia misalnya, telah menjamin urusan pemberdayaan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk “diurus” oleh sebuah kementerian yang saat ini bernama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). India memiliki Ministry of Women and Child Development, Amerika Serikat memiliki the Ministry of Women’s Affaris Restructuring and Empowerement (MORE), dan Korea Selatan bahkan secara eksplisit menyebut isu gender equality ke dalam nomenklatur kementeriannya, yaitu Ministry of Gender Equality and Family (MOGEF).
Pertanyaannya sekarang adalah, apakah segala bentuk upaya baik gerakan maupun eksistensi kelembagaan resmi yang dibiayai oleh pajak rakyat telah berhasil menggugurkan satu per satu isu seksisme yang berada di tengah-tengah masyarakat, terutama di lingkungan kerja?
Perangai Seksisme dalam Lingkungan Kerja
Seksisme oleh Unicef (2014) didefinisikan sebagai prasangka atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin seseorang. Artinya, mengidentifikasi perilaku yang seksis bukan berarti menyudutkan satu jenis kelamin tertentu dan menguntungkan jenis kelamin lainnya. Berbeda dengan konteks feminisme, proporsi dalam menjelaskan isu seksisme tentu saja tidak hanya menitikberatkan keadilan berbasis gender pada kelompok yang sering dianggap marjinal yaitu kelompok perempuan, tetapi juga terhadap kelompok laki-laki. Namun karena hingga saat ini perilaku kekerasan seksual baik verbal maupun fisik masih banyak diderita oleh perempuan, serta budaya patriarki yang masih berurat akar di banyak sendi kehidupan sosial dunia, maka persoalan seksisme menjadi isu yang heavy-nya cenderung kepada kelompok perempuan.
Sejalan dengan konstruksi seksisme yang sedang dibahas dalam artikel ini, saya akan menggunakan social role theory oleh Eagly dan Wood (2016) sebagai instrumen dalam mengelaborasi isu seksime di lingkungan kerja. Social role theory merupakan teori psikologi sosial yang berkaitan dengan distribusi peran sosial perempuan dan laki-laki di dalam lingkungan bermasyarakat. Dalam konteks seksisme di lingkungan kerja, Eagly dan Wood menyebutkan terdapat 3 karakteristik kecenderungan pembagian peran antara perempuan dan laki-laki, yaitu: 1) Women tend to take on more domestic tasks; 2) Women and men often have different occupational roles; dan 3) In occupations, women often have lower status.
Untuk menemukan relevansi pembagian peran sosial berdasarkan teori tersebut secara lebih kontekstual, saya mencoba untuk melakukan riset sederhana melalui instrumen kuisioner dengan sejumlah pertanyaan yang mengangkat isu seksisme di dunia kerja yang merepresentasikan 3 karakteristik tersebut. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner juga diambil secara acak terhadap isu seksisme di lingkungan kerja yang paling sering ditemukan di media sosial maupun laman harian digital. Setiap pertanyaan disajikan dengan pilihan jawaban yang menggunakan Skala Likert, yaitu jawaban dengan 5 pilihan skala. Mesikpun demikian, saya menyadari bahwa riset sederhana ini masih perlu didalami dan didiskusikan kembali dari aspek metode penelitian ilmiah untuk pengembangan kajian selanjutnya.
Secara garis besar, responden yang saya peroleh berjumlah 30 orang, dengan proporsi 72% perempuan dan 28% laki-laki, dengan dominasi usia rata-rata 20 hingga 30 tahun. Mayoritas responden merupakan mereka yang bekerja di institusi pemerintah (90%), disusul dengan pekerja swasta (6,7%), dan pegawai BUMN (3,3%).
Karakteristik #1: Women tend to take on more domestic tasks
Untuk menemukan relevansi karakteristik pertama, saya mengajukan pernyataan dan pertanyaan kepada responden sebagai berikut:
- Pernyataan 1: Urusan domestik rumah tangga (mengasuh anak, mencuci, memasak, dan membersihkan rumah) adalah urusan yang bisa dikerjakan secara bersama-sama baik oleh laki-laki maupun perempuan.
Sebanyak 56% responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Namun di sisi lain, terdapat 44% responden yang seluruhnya perempuan menjawab opsi bisa saja, tapi dominan perempuan.
Kondisi ini secara implisit menyatakan bahwa pola asuh (nurturing) yang ditanamkan sejak kecil bagi perempuan untuk melaksanakan pekerjaan domestik pada prinsipnya sudah tertanam dengan baik dalam diri perempuan. - Pertanyaan 2: Apakah kamu percaya bahwa kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam hal urusan domestik rumah tangga, akan berdampak pada meningkatnya kinerja suami maupun istri di lingkungan kerjanya?
Untuk pertanyaan ini, sebanyak 57% responden memilih sangat percaya, 37% memilih percaya, sedangkan hanya 6% responden yang menjawab biasa saja.
Terhadap kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sudah memahami bahwa pembagian peran yang setara antara suami dan istri di dalam rumah tangga akan meminimalisir konflik (work-family conflict), yang selanjutnya akan bermuara pada meningkatnya kinerja kedua belah pihak di lingkungan kerjanya.
Hal tersebut didukung oleh sebuah riset oleh Brittany Solomon dan Joshua Jackson dari Washington Unveristy dalam May (2015), yang mengungkapkan bahwa kepribadian seseorang maupun kepribadian pasangannya untuk saling bekerja sama dalam urusan domestik adalah dua hal yang saling mempengaruhi dalam kesuksesan berkarir. Salomon dan Jakson menyebutkan:
“…that people with a conscientious spouse may outsource more of the household chores or errands to their partners, thus allowing them to devote more time and energy to work. Less laundry, fewer errands, and reduced responsibility around the house can translate into better pay, greater advancement, and increased job satisfaction.”
Dengan demikian, berdasarkan hasil survey terhadap karakteristik pertama, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyetujui bahwa urusan pekerjaan domestik bukan lagi urusan yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan. Pembagian peran dan kerja sama dalam menuntaskan pekerjaan domestik rumah tangga antara suami dan istri, kelak akan membantu meningkatkan kinerja masing-masing individu di lingkungan pekerjaannya.
Karakteristik #2: Women and men often have different occupational roles
Untuk menemukan relevansi karakteristik ke dua, saya mengajukan pertanyaan kepada responden sebagai berikut:
- Pertanyaan 1: Seberapa sering kamu mendapatkan pekerjaan dengan tingkat kesulitan rendah sampai biasa-biasa saja namun membutuhkan ketelitian (pekerjaan administratif), dan melihat rekan kerjamu (seseorang dengan jenis kelamin berlawanan) mendapatkan pekerjaan dengan tingkat kesulitan sedang sampai sulit (pekerjaan substantif yang menggunakan daya fikir analitis)?
Sebanyak 61% perempuan sepakat bahwa seorang perempuan sering mendapatkan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian seperti pekerjaan administratif, jika dibandingkan dengan laki-laki.
Terhadap porsi kecenderungan pembagian peran ini, seorang responden menyampaikan hal berikut:
“Yang paling menyebalkan adalah ketika atasan banyak memberikan perkerjaan administratif kepada pegawai perempuan dan laki-laki mendapat kesempatan pekerjaan substantif/analitis dan menantang. Seringkali atasan mengucapkan laki-laki memang kurang cocok untuk pekerjaan administratif, padahal jabatan saya dan laki-laki itu sama, harusnya kewajiban dan hak kami pun sama. Sejujurnya pekerjaan administratif yang butuh detail juga pekerjaan yang “sangat” tidak saya sukai dari dulu, hanya saja saya tau bahwa dalam bekerja kita tidak bisa “hanya” mengerjakan hal yang kita sukai, tapi yang sudah jadi kewajiban kita memang harus dikerjakan meskipun tidak kita sukai, kalau tidak lantas siapa yang mengerjakan? Selain itu, pekerjaan administratif terlihat sepele padahal menghabiskan banyak waktu, energi, dan kesabaran. Anehnya beberapa orang bahkan teman perempuan punya mindset seperti itu “cowok ngga bisa kerja administrasi”, kebiasaan ini sangat tidak sehat bagi pengembangan karir pegawai. Di satu sisi perempuan habis energi dan waktunya untuk administratif dan tidak “nampak” kinerjanya.”
Lebih lanjut lagi, salah seorang responden menyampaikan bahwa perilaku seksis tidak hanya terjadi dari laki-laki kepada perempuan ataupun sebaliknya, melainkan sering kali dilakukan oleh sesama gender.
“…seperti contohnya, si A (cewek) punya Bos (cewek). Justru si Bos seringkali lebih memperhatikan pendapat dari bawahannya yang laki-laki. Pekerjaan yang lebih “besar dan penting” diberikan ke laki-laki, sedangkan bawahannya yang perempuan diberi pekerjaan yang rutin dan administratif.“
Namun, salah seorang responden menyampaikan hal yang berbeda. Di kantornya, laki-laki justru cenderung diminta untuk melakukan pekerjaan fisik yang cenderung disepelekan, seperti mengangkat galon air minum. Kondisi ini disebabkan karena distribusi jumlah pegawai laki-laki jauh lebih sedikit jika dibandingkan perempuan, sehinggaa kedudukan perempuan jarang dipandang sebelah mata. Ada yang dirugikan? Tentu saja.
2. Pertanyaan 2: Seberapa sering kamu mendengar atau diminta untuk menegosiasikan sesuatu kepada lawan jenis oleh seseorang dengan gender yang sama dengan target negosiasi? (contoh: Rudi (laki-laki) meminta kepada Ainun (perempuan) untuk bertanya kepada Ahmad (laki-laki) terkait informasi data pegawai di kantor. Hal ini dikarenakan menurut Rudi, kalau perempuan yang minta pasti Ahmad mau.)
Untuk pertanyaan ini, sebanyak 57% responden yang terdiri atas 59% perempuan dan 41% laki-laki menjawab cukup sering, sisanya menjawab jarang, dan hanya 1 orang yang menjawab tidak pernah.
Hal ini mengidikasikan bahwa ketika melakukan negosiasi, keterlibatan faktor gender dalam menyukseskan tujuan negosiasi di lingkungan kerja cukup menjadi faktor penentu. Penelitian lebih komprehensif terkait hal ini pernah dibahas oleh Harvard Law School (2020) dalam daily blog-nya yang berjudul Negotiation, Gender, and Status at the Bargaining Table. Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa when it comes to different characteristics in negotiations, a growing body of research suggests that status consciousness varies depending on the gender of interested parties.
3. Pertanyaan 3: terkait pemakluman yang diberikan oleh lingkungan sekitar ketika laki-laki atau perempuan telat dan malas masuk kerja. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu: 1) Seberapa sering kamu mendengar pemakluman terhadap laki-laki yang telat dan malas masuk kerja dengan argumen umum seperti “ya namanya juga laki-laki” atau “boys will be boys”? dan 2) Seberapa sering kamu mendengar gerutu terhadap perempuan yang telat dan malas masuk kerja dengan argumen umum seperti “Perempuan kok malas”, atau “perempuan masa telat masuk kerja? Harusnya dia bisa bangun lebih pagi”?
Terhadap pertanyaan tersebut, sebanyak 43% responden mengaku jarang mendengar, 23% responden sering mendengar, dan 16% responden tidak pernah mendengar argumen pemakluman terhadap laki-laki ketika mereka telat atau malas masuk kerja.
Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh responden ketika menjawab pertanyaan ke-2 yaitu sikap gerutu dengan ungkapan “perempuan kok malas” yang disampaikan jika perempuan telat atau malas masuk kerja. Dari hasil yang diperoleh, sebanyak total 70% responden menjawab cukup sering mendengar, dan hanya 30% responden yang menjawab jarang mendengar.
Salah seorang responden bahkan menyampaikan hal berikut:
“…Seringkali justru perilaku seksis muncul dari sesama gender, akibat proyeksi pribadi yang ditujukan untuk orang lain dengan gender yang sama. Misal, si Bos (cewek) adalah pribadi yang sangat disiplin, sehingga dia juga berharap bawahannya yang perempuan juga demikian. Sebaliknya, justru si Bos memaklumi kekurangan yg dimiliki oleh bawahan laki-laki.”
Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan pandangan masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan di lingkungan kerja. Notasi peran “perempuan itu harus rajin” sepertinya masih menjadi stereotip gender yang didapat dari cara belajar, budaya, maupun tradisi yang dianut secara turun temurun hingga menjadi hal yang dilegitimasi oleh masyarakat (culturally assigned behavior). Padahal, baik perempuan maupun laki-laki, adalah normal apabila dirundung rasa malas bekerja karena berbagai faktor tertentu, atau disibukkan dengan kegiatan lain sehingga membuat mereka datang terlambat masuk ke kantor. Sifat rajin pun seyogyanya bukan sebuah kata sifat yang melekat bagi satu gender tertentu.
Oleh sebab itu, berdasarkan hasil survey terhadap karakteristik kedua, dapat disimpulkan bahwa kedudukan perempuan di lingkungan kerja mendapatkan porsi yang cukup membingungkan. Mereka tak jarang mendapatkan pekerjaan yang kurang substantif namun membutuhkan ketelitian, melelahkan, bahkan cenderung kurang dianggap, serta secara bersamaan didorong untuk memiliki sifat rajin. Konstruksi ini dapat dikatakan bersumber dari budaya yang secara turun temurun dilegitimasi oleh masyarakat, bahwa wanita adalah wani ditoto (dalam Bahasa Jawa yang artinya berani ditata) untuk menjadi individu yang sabar, teliti, dan rajin.
Namun dalam hal negosiasi, peran perempuan dan laki-laki sama pentingnya. Potensi bargaining keduanya memiliki kedudukan yang setara dan cukup dipertimbangkan apabila ingin melakukan negosiasi, terutama dengan pihak dari gender yang berseberangan.
Karakteristik #3: In occupations, women often have lower status.
Untuk menemukan relevansi karakteristik ke tiga, saya mengajukan pertanyaan kepada responden sebagai berikut:
- Pertanyaan 1: Seberapa sering kamu menemukan ada seorang perempuan dan/atau laki-laki yang secara akademis mumpuni (lulusan universitas bergengsi baik dalam maupun luar negeri), namun tidak/kurang dipandang dan dianggap oleh rekan kerja lainnya terutama dalam pengambilan keputusan?
Terhadap pertanyaan tersebut, diperoleh jawaban sebanyak 47% responden cukup sering menemukan kondisi perempuan yang cakap akademiknya namun kurang diberikan atensi dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan perolehan hanya sebesar 20% responden yang menjawab cukup sering apabila kondisi tersebut terjadi pada laki-laki.
Padahal, keseimbangan porsi dalam pengambilan keputusan bagi laki-laki dan perempuan sebenarnya dapat diidentifikasi secara ilmiah. Mara Mether, seorang neurologis dari University of Southern California dan Ruud van den Bos, neurologis dari University of the Netherlands mengungkapkan bahwa ketika seorang pria sedang berada di bawah tekanan, kecenderungan mereka untuk mengambil resiko (risk hunger) sangat tinggi. Pria akan menjadi fokus kepada reward apa yang akan diperoleh ketika berhasil membuat keputusan seiring dengan meningkatnya level stress yang ditandai dengan meningkatnya detak jantung dan hormon cartisolnya. Mether dan van den Bos mengungkapkan when the pressure is on and there’s the glimmer of a highly rewarding outcome, men take gambles, more and bigger gambles than they would ordinarily choose (Forbes, 2016).
Hal yang berbeda terjadi pada perempuan dalam mengambil keputusan ketika level stress-nya sedang tinggi. Mather dan van den Bos menemukan bahwa ketika tubuh perempuan sedang mengalami reaksi stres yang kuat, mereka mengambil lebih banyak waktu untuk menimbang berbagai kemungkinan dan lebih tertarik pada reward yang lebih kecil namun bisa diandalkan. Ketika stress, perempuan cenderung menjadi risk alert dengan lebih waspada terhadap risiko yang akan terjadi.
Artinya, kesetaraan porsi dan kesempatan dalam proses pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki perlu dibangun secara proporsional dan professional, terlebih lagi jika kedua gender ini sama-sama memiliki kapasitas yang baik dalam hal capaian akademis, maupun prestasi lainnya. Sebagai tambahan, Mather dan van den Bos bahkan menutup pernyataannya dengan kesimpulan:
“…this provides a new reason to have both men and women at the top level when high-stakes decisions are being made. We need both genders in the room to balance one another out when tensions are running high.”
2. Pertanyaan 2:“Seberapa sering kamu mendengar ungkapan “perempuan dan/atau laki-laki ketika sudah berumah tangga pasti akan memiliki keterbatasan atau penurunan kinerja dalam berkarir”?
Melalui pertanyaan tersebut, saya berasumsi bahwa apabila seorang perempuan ataupun laki-laki telah menikah dan menurun kinerjanya, maka dampaknya adalah mereka akan kurang mendapatkan “perhatian” dari lingkungan kerjanya, baik dalam bentuk penugasan penting, penugasan luar kota, penugasan luar negeri, hingga kesempatan promosi.
Terhadap pertanyaan ini, total sebanyak 80% responden menjawab sangat sering, sering, dan cukup sering mendengar pernyataan potensi menurunnya kinerja seorang perempuan ketika berumah tangga. Sebaliknya, sebanyak 63% responden menjawab jarang mendengar dan 20% menjawab tidak pernah mendengar pernyataan bahwa laki-laki akan menurun kinerjanya setelah berumah tangga.
Kondisi tersebut didukung oleh sebuah riset yang dilakukan oleh Mehay dan Bowman (2005) yang menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan pria lajang, pria yang sudah menikah menerima penilaian kinerja yang lebih baik dan jauh lebih signifikan, bahkan cenderung lebih memungkinkan untuk dipromosikan.
Bahkan, sebuah riset terhadap 30 pegawai di 8 casino hotel di Macau terkait kuliatas work-family balance (WFB) menunjukkan bahwa pegawai perempuan mau tidak mau secara kontinu menghadapi kesulitan dalam mewujudkan WFB. Sebaliknya, pegawai laki-laki cenderung mampu untuk mewujudkan WFB karena memiliki kecenderungan emosional untuk berani menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan urusan karir dan rumah tangga, sekaligus bisa bertanggung jawab atas tantangan tersebut.
Terhadap hasil survey terhadap karakteristik ketiga, dapat disimpulkan bahwa isu diskriminasi berbasis gender cukup sering dialami perempuan dalam proses pengambilan keputusan penting di lingkungan kerja, sekalipun mereka memiliki tingkat dan kualitas pendidikan yang baik. Bahkan potensi diskriminasi ini akan semakin meningkat apabila seorang perempuan telah berumah tangga. Kinerjanya sering dianggap berpotensi menurun dan akan berdampak pada berkurangnya berbagai kesempatan yang bisa diperoleh seorang perempuan atas prestasinya.
Quo Vadis Kesetaraan Gender
Melihat hasil survey sederhana di atas, dapat disimpulkan bahwa isu seksis di lingkungan kerja sampai saat ini masih banyak terjadi di kalangan perempuan. Hasil riset dari ILO dalam Woman at Work (2016), menyebutkan bahwa di Asia, Afrika Utara, UEA, dan Amerika Latin jumlah keterserapan perempuan dalam dunia kerja hanya sebesar 46%, sedangkan laki-laki bisa mencapai 72%. Kurang terserapnya tenaga kerja perempuan kebanyakan disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan, skill, serta motivasi yang didukung dengan budaya patriarki yang masih melekat.
Dalam konteks pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Indonesia, sejak tahun 2014 pemerintah telah mengeluarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Secara ringkas, ruang lingkup Perpres tersebut mencakup upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan baik perempuan maupun anak, dan pemberian layanan kebutuhan dasar dan spesifik dalam rangka penanganan konflik. Selain itu juga diatur perihal upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, serta partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian. Melalui Perpres ini, Presiden mengamanatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak kepada seluruh lapisan institusi pemerintahan baik kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Namun yang perlu digaris bawahi adalah, berbagai upaya perlindungan dan pemberdayaan yang dimaksud, hanya ditujukan dalam kondisi spesifik yaitu apabila terjadi konflik sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Lebih lanjut lagi, Kementerian PPPA saat ini memiliki program/kegiatan unggulan pemberdayaan perempuan yang dikenal sebagai 5 isu prioritas Kementerian PPPA. Program tersebut menggunakan strategi pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak yang diinisiasi sejak tahun 2016 dan dilanjutkan hingga saat ini. Secara singkat, program tersebut terdiri dari: 1) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; 2) peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak; 3) penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4) penurunan pekerja anak; dan 5) pencegahan perkawinan anak. Saya berpandangan bahwa agenda tersebut sudah cukup baik karena apabila tersukseskan, maka dampaknya dapat dirasakan secara makro. Namun di sisi lain, secara implisit tergambarkan pula bahwa upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan masih dilakukan di atas permukaan, dan belum secara optimal menjadi bagian yang dengan terang benderang “diselamatkan oleh negara”.
Sekali lagi, isu diskrimnasi berbasis stereotip gender belum diaksentuasi secara eksplisit oleh institusi yang berwenang. Emansipasi adalah semangat kesetaraan dan keadilan yang diglorifikasi, nampaknya belum seutuhnya mampu menginternalisasi sikap kita semua untuk secara sadar saling membuka kesempatan yang seluas-luasnya baik bagi laki-laki maupun perempuan, untuk sama-sama membangun lingkungan kerja yang sehat dan konstruktif.
Secara tradisional, baru isu kekerasan dalam rumah tangga saja-lah yang menjadi parameter tangible perwujudan kekerasan berbasis gender, sedangkan isu seksisme yang cenderung bersifat intangible masih belum mendapat perhatian lebih. Padahal, apabila perilaku seksis secara masif dilakukan, isu yang sifatnya intangible tersebut dapat menjadi hulu dari seluruh perilaku kekerasan fisik berbasis gender yang menjadi hilirnya. Terlebih lagi, perilaku seksis jelas akan memengaruhi psikologis seseorang, memengaruhi kinerja, rasa percaya diri, konflik rumah tangga, tumbuh kembang anak dalam rumah, hingga perekonomian bangsa.
Dengan demikian, saya berpandangan bahwa isu seksisme adalah isu kultural yang harus dibenahi secara komprehensif, bukan hanya melalui jalur kultural, tetapi juga secara struktural melalui formulasi dan impelementasi kebijakan yang berbasis isu, implementatif, dan tepat sasaran. Sedangkan pembenahan secara kultural yakni melalui upaya meningkatkan pemahaman dan mengampanyekan berbagai contoh perangai seksis di lingkungan kerja, dampak psikologis yang ditimbulkan dari perilaku seksis, sambil juga membudayakan upaya peningkatan awareness tersebut.
Mengapa pembenahan kultural dan struktural atas isu seksisme harus dimulai dari lingkungan kerja? Saya berpendapat bahwa seseorang yang “berhasil terserap” dalam ekosistem pekerja, adalah mereka yang teseleksi secara sistematis, memiliki tingkat pendidikan minimal sederajat, memiliki kehidupan sosial yang terbuka, otonom, berswadaya, dan bersedia mengikatkan diri pada tatanan legal maupun seperangkat norma yang diakui bersama. Para pekerja ini merupakan manifestasi atas masyarakat madani sehingga dinilai mampu membawa perubahan di lingkungan sekitarnya.
Seksisme kehadirannya seperti angin, tidak terlihat namun dapat dirasakan. Apabila angin tersebut berhembus begitu kencang dan cepat, dampaknya jelas bisa merusak tatanan yang sudah terbangun. Satu hal yang perlu kita sepakati bersama adalah, lelah menjaga dan memercantik tatanan yang sudah terbangun pada prinsipnya jauh lebih murah dan menyenangkan daripada membangun kembali suatu tatanan.
Selamat hari Kartini!
Referensi:
- Eagly, A. H., & Wood, W. (2016). Social Role Theory of Sex Differences. In N. Naples, R. C. Hoogland, M. Wickramasinghe, & W. C. A. Wong (Eds.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies
- Forbes. 2016. How Decision-Making Is Different Between Men And Women And Why It Matters In Business
- Forbes. 2013. How To Ace The 50 Most Common Interview Questions
- Harvard Law School, (2020), Negotiation, Gender, and Status at the Bargaining Table.
- ILO, 2016, Woman at Work
- May, Cindi. 2015. For Couples, Success at Work is Affected by Partner’s Personality: Researcher Identify the Personality Traits that Plays a Positive Role, dalam scientificamerican.com
- Mehay, Stephen L. and Bowman R. William. 2005. Marital Status and Productivity: Evidence from Personnel Data. Southern Economic Journal, Vol. 72, No. 1 (Jul., 2005), pp. 63-77
- Suk Ha, Yun Kit Ip, et.al. 2018. Do Single and Married Females Have the Same Standard of Work–Family Balance? Case Study of Frontline Employees in Macau. Journal of Toursim and Hospitality.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Unicef (2014)
- UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Divisi Sembari Dinas, Abdimuda Indonesia
Analis di Kementerian PANRB